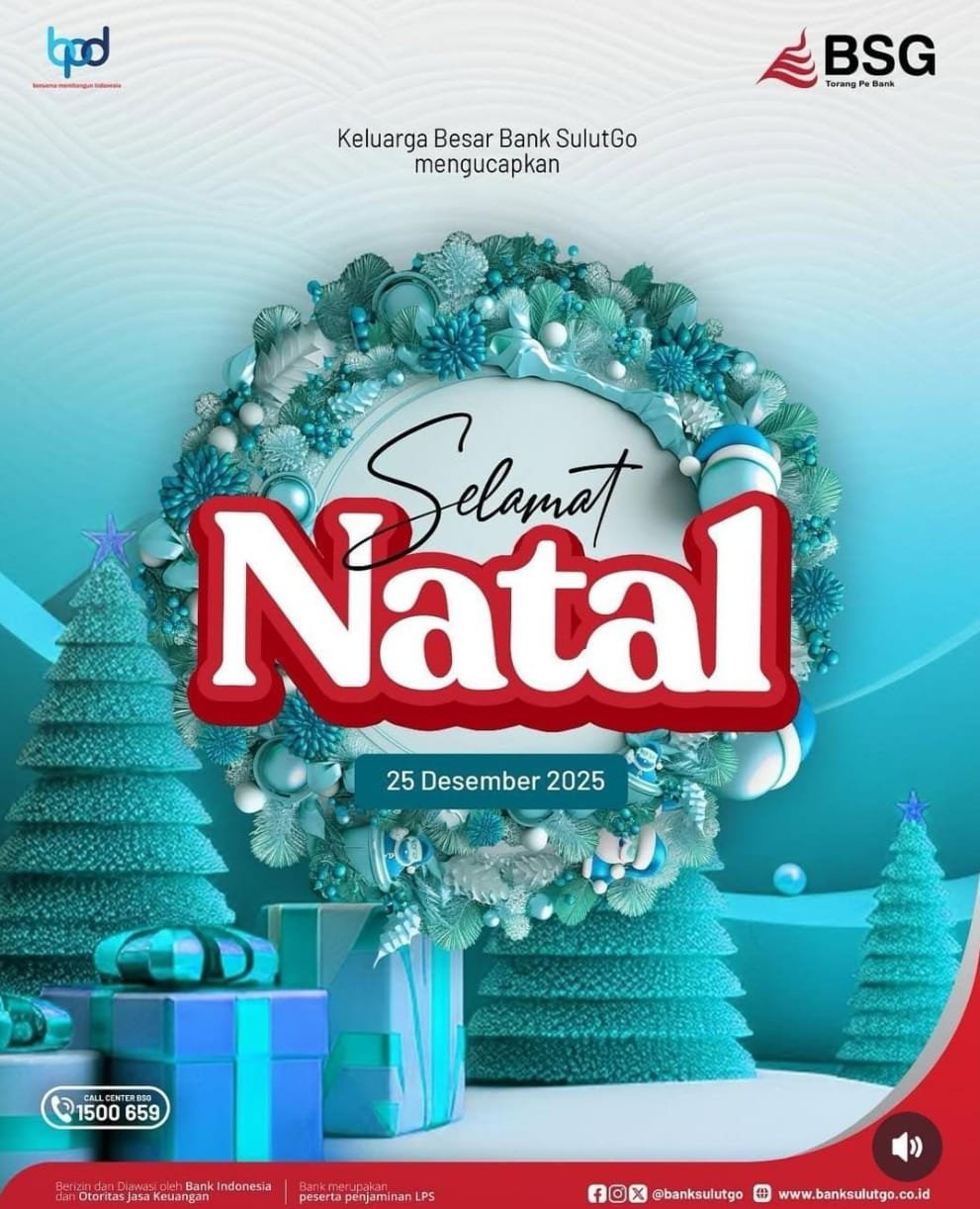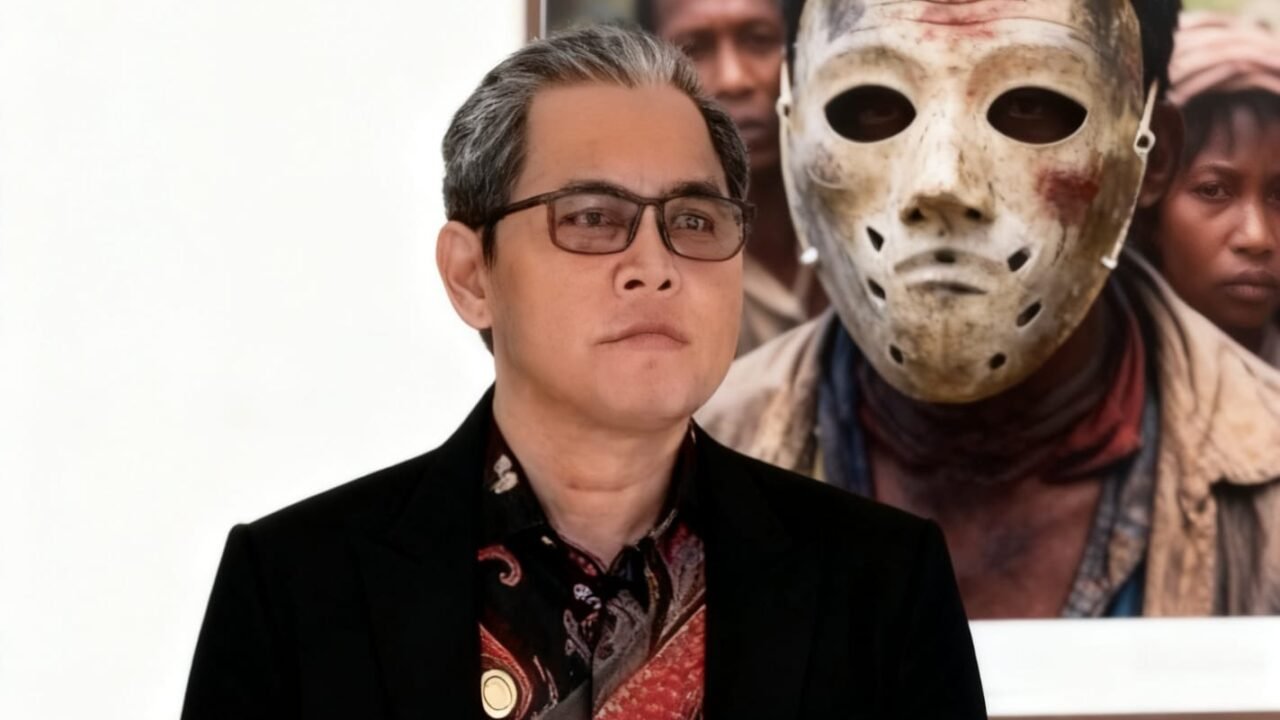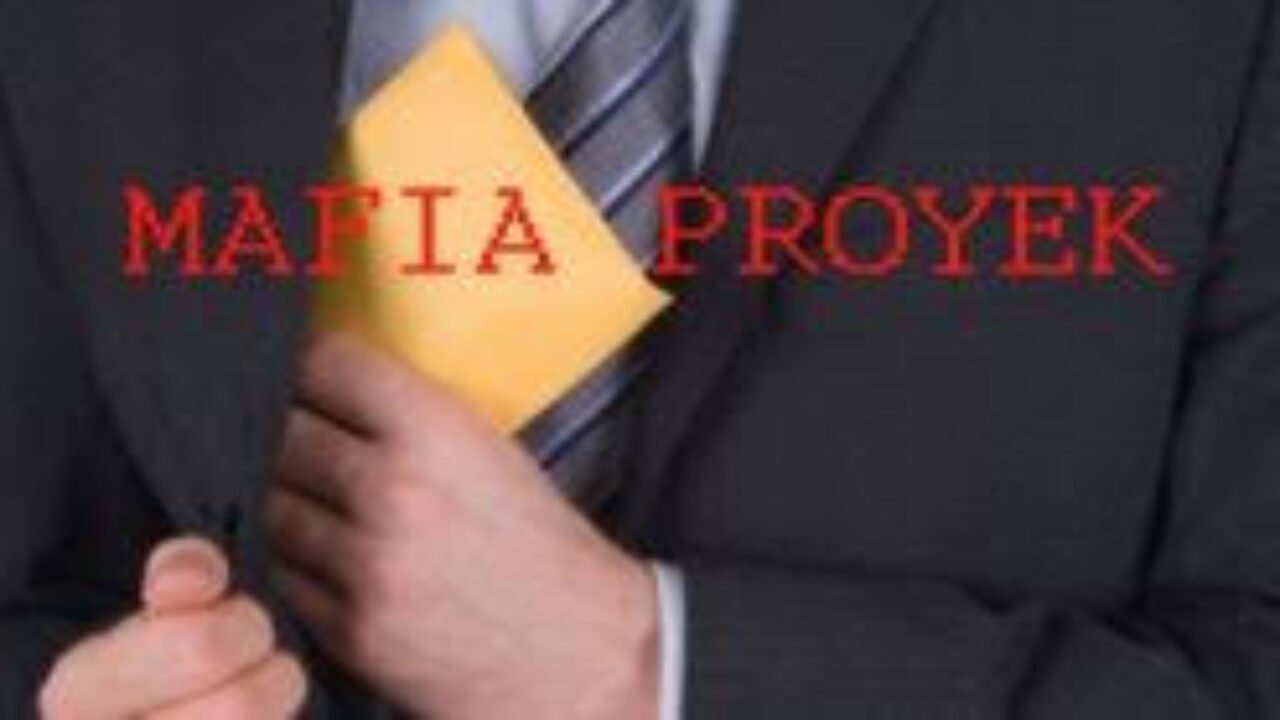Oleh: Dr. Agatha Jumiati, S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Beberapa hari terakhir, jagat media sosial ramai memperbincangkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terekam kamera dengan ekspresi wajah dinilai mencibir para pendemo. Video itu beredar cepat, menuai kecaman publik, dan akhirnya berujung pada permintaan maaf resmi sang anggota dewan. Yang menarik, ini bukan soal ucapan atau keputusan politik, tetapi soal ekspresi wajah dimana hal tersebut mungkin tidak disengaja, namun berdampak luas di ruang digital.
Kasus ini mengajarkan satu hal penting yakni dalam dunia politik modern, badan bisa diam, tapi wajah tetap bisa bersuara. Dan ketika suara itu dianggap menghina rakyat, maka hukum etika pejabat publik ikut bicara.
Sebagai pejabat publik, anggota DPRD bukan hanya pelaksana fungsi legislasi, tapi juga simbol perilaku negara di mata rakyat. Oleh karena itu, mereka terikat oleh kode etik dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Dalam konteks ini, “mimik wajah mencibir” bukan sekadar ekspresi personal, tetapi bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap: asas kepantasan dan kepatutan (propriety) juga asas pelayanan publik yang berorientasi pada penghormatan terhadap warga negara.
Selain itu, Peraturan DPRD tentang Kode Etik di setiap daerah umumnya mengatur bahwa anggota dewan wajib: “Menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga DPRD.” Maka ketika wajah menjadi simbol kesombongan kekuasaan, kepercayaan publik terhadap lembaga ikut runtuh.
Memang, tidak ada pasal yang bisa menjerat “ekspresi wajah mencibir” dalam hukum pidana atau administrasi. Namun dalam perspektif hukum publik, perilaku pejabat negara harus diukur dengan standar martabat jabatan. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), di antaranya: Asas kepastian hukum, Asas kecermatan, Asas ketidakberpihakan, Asas kesopanan dan kepatutan.
Artinya, walau tidak melanggar hukum secara formil, sikap atau ekspresi yang melukai rasa hormat publik tetap bisa dinilai sebagai pelanggaran asas kesopanan jabatan. Sama seperti hakim, polisi, atau ASN yang diatur dalam kode etik profesi, anggota DPRD juga wajib menjaga kehormatan jabatan, bukan sekadar menghindari pidana.
Kasus ini juga memperlihatkan fenomena hukum modern: “trial by social media.” Masyarakat kini menjadi hakim instan di ruang digital dengan memberi vonis hanya dari cuplikan video beberapa detik. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya. Sebab dalam demokrasi digital, rakyat memang punya hak kontrol sosial terhadap pejabat publik (Pasal 28F UUD 1945). Namun, di sisi lain, viralitas sering mengabaikan asas proporsionalitas dan konteks.
Di sinilah peran hukum etika menjadi penting: bukan untuk menghukum, tetapi menjadi penuntun perilaku agar pejabat sadar bahwa di era media sosial, setiap gerak tubuh adalah pernyataan politik.
Langkah anggota DPRD yang meminta maaf secara terbuka patut diapresiasi. Dalam konteks hukum moral, itu adalah bentuk tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai good governance. Permintaan maaf bukan tanda kelemahan, tetapi kesadaran akan konsekuensi jabatan public bahwa mereka hidup di bawah sorotan rakyat yang membayar gajinya.
Namun, permintaan maaf saja tidak cukup. Lembaga DPRD seharusnya menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran kelembagaan, dengan:
· Menguatkan kode etik dan pelatihan etika publik bagi seluruh anggota,
· Mendorong agar badan kehormatan DPRD bersikap aktif dalam menangani isu reputasi publik,
· Menegaskan bahwa martabat jabatan lebih berharga daripada pembelaan ego pribadi.
Publik tidak menuntut pejabatnya sempurna. Mereka tahu bahwa manusia bisa salah, bisa salah ucap, bahkan salah ekspresi. Namun yang dibutuhkan adalah rasa hormat, empati, dan kesadaran diri bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan panggung. Senyum yang salah tempat bisa menjadi bencana citra.
Dan di era digital, satu frame bisa menghapus kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Kekuasaan tanpa empati adalah tirani kecil. Etika publik adalah hukum tak tertulis yang nilainya lebih tinggi dari undang-undang.
Kasus “mimik mencibir pendemo” ini tampak sepele, tapi ia memperlihatkan krisis empati dalam relasi pejabat dan rakyat. Di tengah ketidakpercayaan terhadap lembaga politik, seharusnya setiap wakil rakyat memahami bahwa tanggung jawab moral adalah hukum tertinggi. Hukum positif mungkin tak bisa menghukum ekspresi wajah, tapi hukum moral dan sosial selalu punya cara menilai: melalui opini publik, kehilangan wibawa, dan erosi kepercayaan.
Maka, pelajaran terbesarnya adalah dalam dunia digital, pejabat publik bukan hanya harus berhati-hati dalam berbicara, tapi juga dalam diam bahkan dalam tersenyum.